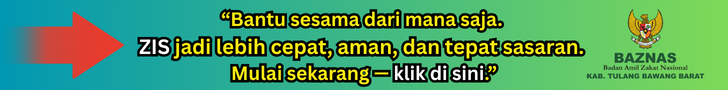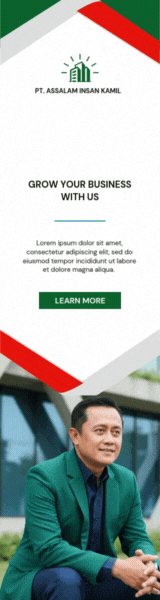TAJUK Teras informasi — Wacana Kepala Daerah dipilih oleh DPRD menjadi diskursus yang hangat dalam beberapa hari ini, di tengah suasana duka akibat bencana alam yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Pro kontra pasti muncul memaknai wacana politik pengembalian Pilkada melalui DPRD. Padahal sesungguhnya, Kepala Daerah dipilih DPRD bukanlah hal baru dalam sejarah politik Indonesia.
Pada era Otoritarianisme Militeristik Politik Orde Baru di bawah Soeharto, selama hampir 32 tahun, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.
Semua orang tahu bahwa siapapun yang dikehendaki Pemerintah Pusat saat itu pasti akan terpilih. DPRD hanya berfungsi sebagai ketok palu. Rata-rata kepala daerah diambil dari kalangan ABRI, sementara kelompok sipil termarginalkan.
Pada masa transisi Reformasi 1998 hingga pemerintahan Megawati, mekanisme Kepala Daerah dipilih DPRD masih berlangsung. Baru pada masa SBY, Kepala Daerah mulai dipilih langsung oleh rakyat.
Namun ide dan gagasan bedar Pilkada langsung itu justru lahir pada masa Megawati, ditandai dengan hadirnya UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.
Alasan yang digunakan untuk mengembalikan pemilihan Kepala Daerah kepada DPRD hari ini hanya berkutat pada satu hal: high cost social dari Pilkada langsung dianggap terlalu besar.
Money politik terjadi di mana-mana, masyarakat terpecah belah karena perbedaan pilihan, dan akhirnya banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi. Inilah alasan yang selalu dilontarkan.
Namun harus diakui, Pilkada langsung memang sarat dengan praktik money politik. Bahkan dalam pemilihan legislatif sekalipun, para calon anggota DPRD yang terpilih mayoritas juga menjalankan praktik money politik.
Jika rumusnya adalah bahwa tingginya biaya sosial Pilkada langsung (baca: money politik) menjadi alasan pembenar, maka seharusnya lembaga yang wajib disalahkan dan bahkan patut dibubarkan adalah penyelenggara pemilu.
Mereka yang bertanggung jawab menjaga marwah dan kualitas Pilkada langsung justru dalam banyak kasus gagal menjalankannya. Prakteknya, banyak oknum penyelenggara pemilu Pilkada yang diam-diam menjadi bagian dari tim sukses.
Fenomena ini bukan rahasia dan menjadi cerita umum di setiap Pilkada. Pilkada langsung memang penuh barang busuk berupa money politik, sesuatu yang harus kita akui bersama karena mencederai demokrasi.
Namun memindahkan pemilihan Kepala Daerah ke DPRD sama saja memindahkan barang busuk ke tempat yang lebih busuk. Money politik bukan hilang, melainkan bergeser ke ruang-ruang gelap di gedung DPRD.
Moralitas politik hari ini di kalangan Anggota Dewan sangat memprihatinkan. Dan sulit dibayangkan apa jadinya jika Kepala Daerah dipilih oleh DPRD. Uang miliaran pasti berhamburan. Siapa yang menikmati?
Bisa jadi harga satu suara anggota DPRD dalam pemilihan Kepala Daerah mencapai Rp1 miliar atau lebih, jika mekanisme itu kembali diberlakukan. Bandingkan dengan “harga” suara rakyat biasa dalam Pilkada langsung yang hanya 50 ribu–100 ribu.
Sekali lagi mengembalikan pemilihan Kepala Daerah kepada DPRD bukan solusi. Itu hanya memindahkan bau busuk dari satu ruang ke ruang lain yang jauh lebih pengap dan lebih busuk.
Penulis : Ahmad Basri : Ketua Kajian Kritis Kebijakan Pembangunan (K3PP)
Editor : Ahmad Sobirin