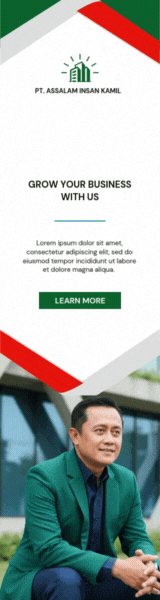TERAS INFORMASI — Dalam konteks pasca-Perang Dingin, pola kemunduran demokrasi menunjukkan karakteristik berbeda dibanding periode sebelumnya. Menurut Bermeo (2019), Lust dan Waldner, serta Lührman dan Lindberg, pola ini ditandai oleh dua ciri utama: pertama, berlangsung secara bertahap dan inkremental (tidak seperti kerusakan tiba-tiba seperti kudeta atau revolusi yang umum di abad 20); kedua, dilaksanakan oleh aktor politik terpilih sah menggunakan kerangka kerja yang tampak legal, sehingga otoritarianisme berkembang di bawah kedok demokrasi.
PERGESERAN PARADIGMA DEMOKRASI LOKAL INDONESIA
Pasca-rezim Soeharto yang berkuasa selama tiga dekade dengan sistem sentralistik dan otoriter, paradigma demokrasi lokal beralih menjadi lebih partisipatif sebagai capaian desentralisasi dan demokratisasi. Namun, kurang dari seperempat abad setelah Reformasi, muncul masalah baru.
Pada tahun 2022-2023, Presiden Joko Widodo menunjuk 271 kepala daerah sebagai Penjabat (Pj) untuk periode panjang, menciptakan “demokrasi tanpa pemilihan” tanpa kontrak politik antara pemimpin dan warga. Kini, di masa pemerintahan Prabowo Subianto, muncul wacana Pilkada melalui mekanisme DPR/DPRD.
Kedua kebijakan ini bukan terpisah, melainkan bagian dari kesinambungan logika kekuasaan yang sama: penguatan kontrol elite dan pelemahan partisipasi rakyat atas nama stabilitas dan efisiensi. Hal ini menggeser sumber legitimasi dari rakyat ke negara administratif, yang bertentangan dengan teori demokrasi Robert A. Dahl yang menekankan partisipasi efektif dan kontrol rakyat atas agenda politik.
JEBAKAN DEMOKRASI PROSEDURAL
Secara konstitusional, Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 hanya menyebutkan kepala daerah dipilih secara demokratis tanpa merinci mekanismenya. Meskipun pemilihan melalui DPRD secara teori merupakan bentuk kedaulatan rakyat karena DPRD hasil pemilu, perubahan mekanisme akan berdampak pada pertarungan politik lokal.
Pilkada tidak lagi menjadi arena bagi ide dan gagasan yang disaksikan rakyat, melainkan negosiasi antar elit politik terbatas. Hal ini akan menimbulkan dua masalah serius: akuntabilitas pemerintahan hanya tertuju pada DPRD (bukan masyarakat luas), dan politik uang akan bergeser dari membeli suara rakyat ke membeli dukungan elit politik.
Demokrasi prosedural dapat berjalan rapi secara formal, namun jika substansi kedaulatan rakyat dikosongkan, ia akan berubah menjadi instrumen kontrol. Rakyat tidak lagi sebagai pemilik kedaulatan, melainkan objek yang harus dikelola.
POLITIK UANG SEBAGAI ALIBI KEKUASAAN
Narasi pemberantasan politik uang digunakan sebagai justifikasi utama wacana Pilkada DPR/DPRD. Namun, fenomena politik uang marak pasca-penerapan sistem pemilu proporsional terbuka pada 2009, dengan data menunjukkan peningkatan perilaku permisif masyarakat dari sekitar 33% pada 2019 menjadi 46,96% pada 2024 (IndikatorPolitik, 2024).
Sistem yang seharusnya membuka partisipasi justru memperluas transaksi uang yang harus dikeluarkan calon, antara lain:
– Ongkos pra-pencalonan (mahar politik, biaya lobi, survei elektabilitas)
– Ongkos kampanye (alat peraga, iklan, tim sukses)
– Ongkos elektoral informal (politik uang, bantuan sosial berlabel)
– Ongkos pasca-terpilih (balas budi, pengamanan posisi)
Alih-alih memberantas politik uang, perubahan mekanisme hanya akan memindahkan transaksi dari ruang publik ke ruang elite, membuat korupsi lebih efisien dan tertutup.
IMPLIKASI JANGKA PANJANG: DEMOKRASI ELITIS-ADMINISTRATIF
Kesinambungan kebijakan Jokowi dan Prabowo berpotensi menghasilkan bentuk baru demokrasi Indonesia yang berwatak otokratis secara substantif, meski tetap mempertahankan prosedur formal. Kekuasaan eksekutif semakin dominan melalui sentralisasi kebijakan, pelemahan lembaga pengawas, dan kontrol terhadap kritik. Oposisi politik cenderung dikooptasi, membuat ruang alternatif politik semakin sempit.
Selain itu, demokrasi Indonesia semakin dipengaruhi oleh oligarki ekonomi. Biaya politik yang tinggi membuat kontestasi bergantung pada modal besar, sehingga kebijakan publik lebih responsif terhadap kepentingan elite. Kondisi ini disebut sebagai demokrasi elektoral iliberal atau otokrasi elektoral, yang berpotensi menjauhkan demokrasi dari cita-cita Reformasi.
CARA MENUJU DEMOKRASI SUBSTANSIAL
Perbaikan demokrasi harus diarahkan pada pembatasan kekuasaan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Menurut Rousseau (1762), sumber legitimasi politik terletak pada kehendak kolektif warga negara, dengan membedakan konsep kedaulatan (milik rakyat) dan pemerintahan (pelaksana kehendak kolektif).
Pembatasan kekuasaan tidak hanya bergantung pada mekanisme institusional, melainkan pada partisipasi aktif warga dalam pembentukan hukum dan pengawasan politik. Hanya dengan demikian, hukum tidak akan berubah menjadi alat dominasi dan kebebasan politik dapat terwujud.
DAFTAR PUSTAKA:
1. Selamat Datang Otokrasi (2024)
2. Rousseau, Jean-Jacques. Du contrat social ou Principes du droit politique (1762)
3. Demokrasi dan para pengkritiknya (2001)
4. Geertz, Clifford. 1980. Negara dan Penjaja. Jakarta: PT Gramedia
5. Gould, Charles. 1998. Demokrasi Ditinjau Kembali. Jakarta: PT Gramedia
Penulis : Hariyadi Sudibyo
Editor : Ahmad Sobirin
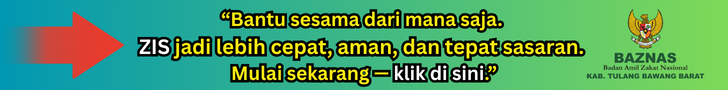



.png)